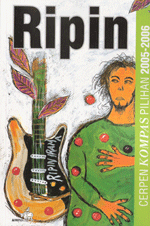Eko Prasteyo dalam buku ini memaparkan mengapa demokrasi yang diterapkan di Negeri ini telah menyimpang dari cita-citanya, yakni kedaulatan rakyat. Sebaliknya, kenyataan mengatakan bahwa rakyat justru semakin mengalami keterpurukan, tidak berdaya, dan semakin termarginalkan. Buku ini seolah hadir sebagai bentuk protes dan ungkapan rasa kecewa karena perubahan politik yang berada di bawah bendera demokrasi telah gagal dalam memenuhi janjinya.
Pertama, janji keberpihakan pada rakyat kian susah dicapai. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan justru semakin terpinggirkan dengan kebijakan pemotongan subsidi, kenaikan BBM, hingga penggusuran pada perumahan rakyat miskin, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Dalam pengambilan kebijakan itu, rakyat semakin tidak dilibatkan. Kedua, menyangkut pranata hukum yang kian buruk kinerjanya. Tidak ada kepastian dan ketegasan hukum. Banyak pejabat tinggi yang menjadi tersangka koruptor tetapi bisa lepas dari jerat pengadilan. Pelanggaran HAM yang melibatkan militer makin kian susah diusut. Ketiga, menyangkut kredibilitas pihak swasta yang tidak terlalu mengagumkan. Sebagian kebijakan publik yang diserahkan ke sektor swasta berubah menjadi penguasaan oleh pasar. Keempat, menyangkut beberapa aktivis pro demokrasi yang mengkomersialkan program demokrasi.
Akibatnya, bukan kepentingan rakyat yang mau dibela melainkan keuntungan pribadi atau pun kelompok. Paparan soal demokrasi dalam buku ini cukup runtut dan mudah diikuti.
Buku ini memaparkan pula kajian tentang bagaimana demokrasi diterapkan di Negeri ini. Demokrasi hanya dijadikan kedok dan senjata kampiun untuk membuai rakyat. Banyak pihak yang memanfaatkan demokrasi hanya untuk mengeruk keuntungannya sendiri. Eko Prasetyo dengan tegas menyebutnya dengan kawanan para bandit. Ambil contoh, Pemilu menjadi ajang kawanan politisi mengumbar janji-janji demokrasi dengan sibuk mengunjungi dan berdialog dengan rakyat. Tapi, setelah pemilu usai dan kekuasaan dipegang, kunjungan dan dialog itu juga terhenti.
Jatuhnya demokrasi pada tangan para bandit disebabkan karena partisipasi rakyat sekadar janji belaka. Olle Torquist, pengamat politik, seperti tertulis dalam buku ini (hlm. 44) mengatakan, “...jikalau demokrasi yang terjadi hanya secara formal dalam artian tidak diiringi oleh partisipasi yang sungguh-sungguh dari rakyat maka hasil yang mungkin terlihat merupakan ‘demokrasi kaum penjahat.
Di depan kekuasaan para bandit itu, peran oposisi sebagai salah satu elemen alternatif kekuasaan demokrasi digambarkan loyo dalam buku ini. Banyak kalangan aktivis yang meneriakkan perlawanan, kemudian terjatuh dalam pelukan pihak donor. Bahkan, yang lebih menyakitkan lagi deretan para aktivis yang dulu menjadi pelopor melawan rezim lama, kini malah duduk dan menumpang dalam partai politik yang dikecam. Tidak hanya aktivis LSM, tapi juga gerakan mahasiswa dan kaum intelektual. Dari liak-liuk perjalanan demokrasi ini, Eko Prasetyo dalam bab IV menyimpulkan bahwa rakyat bukannya dilayani demokrasi, tetapi hanya menjadi pelayan demokrasi. Rakyat hanya menjadi barisan kata yang menjadi berarti ketika ada pesta demokrasi. Rakyat disingkirkan dan dimarginalkan. Partai-partai politik yang menjamur hanyalah siap mengeruk keuntungan daripada melakukan perubahan yang berguna untuk rakyat.
Dalam bab terakhirnya, buku ini memaparkan langkah-langkah dan strategi konkrit bagaimana merebut demokrasi dari tangan para bandit. Inilah yang menjadi nilai tambah buku ini. Maksudnya, buku ini tidak hanya piawai dalam membedah dan menganalisis persoalan, melainkan juga memberi solusi atau langkah alternatif untuk mengatasi persoalan itu.
Ada sepuluh langkah dan strategi. Pertama, lewat jalur pendidikan. Pendidikan merupakan jalan utama untuk memperkuat kesadaran tentang bagaimana implementasi demokrasi kerakyatan itu dibentuk. Kedua, membentuk organ gerakan yang mempunyai visi dan metode yang sesuai dengan syarat-syarat sosial dan kultural. Ketiga, memberdayakan peran advokasi dan pembelaan untuk masuk sekaligus memperebutkan aspek legalitas. Keempat, memberdayakan media terutama dalam memperkuat pencitraan sekaligus pengungkapan informasi akurat tentang nasib rakyat. Kelima, pentingnya mengembangkan jaringan antar kelompok etnis maupun agama. Keenam, sudah saatnya mengembangkan tradisi yang berbasis pada produksi. Ketujuh, mengadakan gerakan pelayanan publik yang kini tidak dilakukan negara. Kedelapan, perlu dikembangkannya tradisi kaderisasi yang berbasis pada masa rakyat riil. Kesembilan, pendokumentasian dan pendataan semua kegiatan dan peristiwa yang terjadi. Kesepuluh, melakukan penggalangan massa untuk aksi turun ke jalan sebagai langkah terakhir.
Secara keseluruhan buku ini cukup mengusik dan menarik. Mengusik karena mempertanyakan kembali jargon-jargon demokrasi yang mengusung kedaulatan rakyat tetapi pada kenyataannya justru rakyat semakin ditinggalkan. Menarik karena buku ini secara tidak langsung memaparkan sebuah hasil analisis sosial dan pengamatan yang jeli pada sejarah demokratisasi di Indonesia. Oleh karena itu, buku ini layak dibaca oleh siapa saja, termasuk para aktivis pejuang demokrasi, pemerintah, maupun rakyat jelata. Paling tidak, dengan membaca buku ini, kita bisa tahu demokrasi seperti apa dan demokrasi untuk siapa?
Musafir Muda